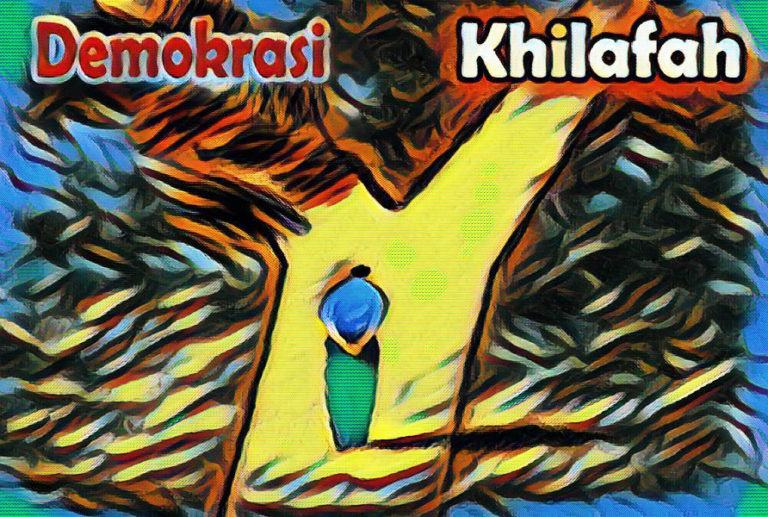Pertanyaan mengenai apakah Indonesia bisa menganut sistem negara Khilafah bukanlah persoalan baru. Banyak organisasi dan tokoh pemikir di Indonesia telah lama bergumul dengan istilah ini, termasuk Cak Nur, Gus Dur, dan Muhammad Abduh. Di Indonesia, beberapa kelompok seperti Negara Islam Indonesia (NII), juga dikenal sebagai Darul Islam (DI), pernah mencoba mendirikan negara berdasarkan Khilafah. Darul Islam diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Tasikmalaya, Jawa Barat (Irfan S. Awwas, 2009).
Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), yang lahir dari Kongres Mujahidin I di Yogyakarta pada 5-7 Agustus 2000, juga merupakan organisasi yang menginginkan penerapan Syariat Islam di Indonesia. Kongres ini dihadiri lebih dari 1.800 peserta dari 24 provinsi di Indonesia dan beberapa utusan dari luar negeri. Kongres ini menghasilkan mandat kepada 32 tokoh Islam Indonesia yang tergabung dalam Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) untuk melanjutkan misi penegakan Syariat Islam melalui wadah yang dikenal sebagai Majelis Mujahidin (Irfan Suryahardi Awwas, 2001). Organisasi lain seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga tak ketinggalan dalam memperjuangkan ide Khilafah.
Dari berbagai literatur yang penulis pelajari, dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidak mungkin menganut sistem Khilafah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa cita-cita HTI untuk menegakkan Khilafah di Indonesia, dengan menggantikan sistem demokrasi yang ada, bertentangan dengan realitas sosial, politik, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Ide HTI bukan hanya menegakkan Syariat Islam, tetapi juga mengubah sistem pemerintahan secara total.
Jika Khilafah adalah sarana untuk menegakkan Syariat Islam, maka penting untuk disadari bahwa Syariat Islam sudah dapat diterapkan di Indonesia sesuai dengan keyakinan umat Islam. Contohnya, dalam hukum perkawinan, undang-undang menyatakan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan sesuai keyakinan agama masing-masing, dan kemudian dicatatkan ke negara. Bagi umat Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara bagi non-Muslim di Kantor Catatan Sipil. UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama juga merupakan salah satu undang-undang yang didasarkan pada hukum Islam. Ada juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sejumlah regulasi lainnya yang mengakomodasi hukum Islam.
Penulis berpendapat bahwa argumen tentang Khilafah ini juga didukung oleh pendapat dari berbagai organisasi Islam besar di Indonesia, seperti Al Washliyah dan Nahdatul Ulama (NU). Mereka secara tegas menolak ide Khilafah sebagai kewajiban mutlak bagi umat Islam. Sebagai contoh, Sa’id bin Jumhan mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Safinah, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Pemerintahan Khilafah pada umatku akan berlangsung selama tiga puluh tahun, setelah itu akan dipimpin oleh pemerintahan kerajaan.” Safinah merinci masa pemerintahan para Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ra), yang semuanya berlangsung selama 30 tahun.
Hadits tersebut menunjukkan bahwa Khilafah yang sejati, yang sesuai dengan ajaran kenabian dan menerapkan Syariat Islam secara sempurna, hanya berlangsung selama masa Khulafaur Rasyidin. Setelah itu, meskipun para pemimpin berikutnya menyandang gelar khalifah, pemerintahan mereka lebih menyerupai sistem kerajaan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran kenabian. Masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Utsmani lebih merupakan kerajaan daripada Khilafah yang murni.
Kesimpulan penulis adalah bahwa Khilafah bukanlah kewajiban yang mutlak harus ditegakkan. Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, secara tegas menolak paham yang memutlakkan sistem Khilafah dan menganggapnya satu-satunya pilihan politik Islam yang sah. Muhammadiyah menekankan bahwa Pancasila adalah hasil konsensus nasional dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Negara Pancasila disebut sebagai “Dar al-Ahdi” (negara konsensus) dan “Dar al-Syahadah” (negara kesaksian), di mana umat Islam bisa bebas melaksanakan ibadah dan Syariat Islam tanpa hambatan.
Hal yang sama ditegaskan oleh Al Washliyah, yang menyatakan bahwa NKRI adalah harga mati. Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amin, juga pernah menyatakan bahwa Pancasila adalah solusi kebangsaan yang mengakomodasi nilai-nilai Islam dan menjadi titik temu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Secara historis, tidak ada sistem pemerintahan yang sempurna, baik itu demokrasi maupun Khilafah. Bahkan di antara Khulafaur Rasyidin, hanya Abu Bakar Ash-Shiddiq yang meninggal secara alami, sementara Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib semuanya meninggal akibat kekerasan politik. Ini menunjukkan bahwa sistem Khilafah pun tidak kebal terhadap konflik internal dan pergolakan politik.
Sistem pemerintahan Khilafah, dalam konteks sejarahnya, hanyalah salah satu bentuk pemerintahan yang populer pada zamannya, seperti halnya kerajaan dan kesultanan. Islam tidak memiliki keharusan untuk meniru sistem ini, terutama jika ada alternatif yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks lokal.
Kesimpulan
Khilafah bukanlah kewajiban mutlak yang harus ditegakkan, melainkan salah satu pilihan dalam sistem pemerintahan. Dalil-dalil yang mendukung kewajiban Khilafah sering kali bersifat bisyarah (ramalan), bukan perintah yang harus dilaksanakan. Dalam konteks Indonesia, yang sudah memiliki sistem demokrasi yang stabil dan memungkinkan umat Islam menjalankan Syariat secara bebas, upaya untuk menggantikan demokrasi dengan Khilafah adalah tindakan yang berlebihan dan tidak realistis.
Urgensi pemerintahan Islam di Indonesia terletak pada kemampuan umat Islam untuk menjalankan agamanya dengan bebas, dan hal ini sudah difasilitasi oleh negara. Tidak ada alasan kuat untuk merombak sistem yang ada, apalagi jika perubahan tersebut dapat memicu konflik dan ketidakstabilan.